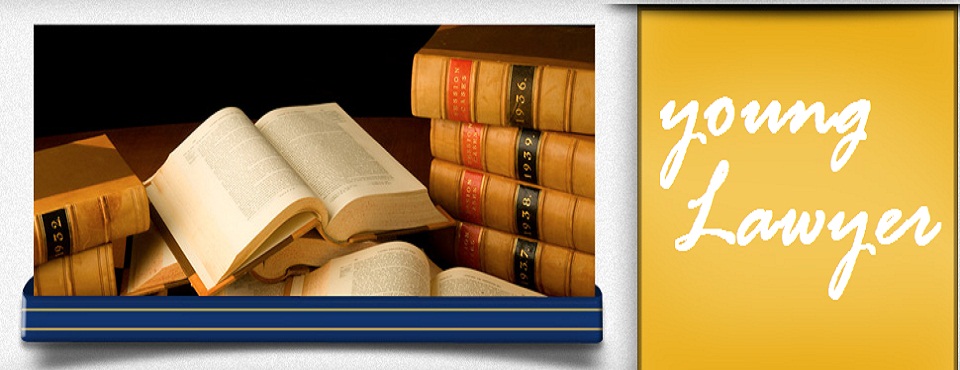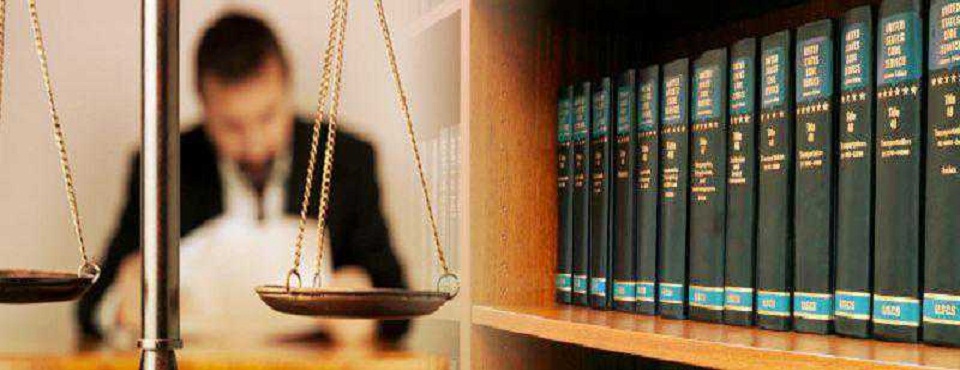Tunjangan
Hari Raya[1]
By.
Junaiding[2]
Dasar
Hukum
THR sering menjadi isu dan masalah
di kalangan buruh dan pengusaha, akan tetapi kita harus rela mengelus dada
dengan lemahnya dan rendahnya kekuatan hukum yang mengatur. Untuk penegak hukum
khususnya para lawyer atau pengacara yang memiliki klien dengan kasus semacam
ini maka haruslah memiliki stategi-stategi tertentu dalam menanganinya.
Meskipun UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disahkan namun
tidak ada dalam satu pasalpun disinggung terkait dengan THR.[3]
Sehingga mau atau tidak mau kita harus mengacu kepada Permen Tenaga Kerja dan
Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja
di Perusahaan.[4]
Kadang kala setiap tahunnya Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi mengeluarkan
Surat Edaran terkait dengan THR seperti misalnya Surat Edaran Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No. SE. 05/MEN/VII/2012 tentang Pembayaran Tunjangan
Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama, atau Surat Edaran (SE) Nomor SE.03/MEN/VII/2013 tentang
Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbuan Mudik Lebaran Bersama.
Namun perlu diketahui bahwa Surat Edaran hanyalah berisi himbauan dan hanya
berlaku di kalangan internal saja, tidak berlaku keluar.[5]
Oleh karena itu, untuk sekarang ini, yang menjadi pedoman pembayaran THR
yakni Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 Tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.
Definisi
dan Makna
Pasal
1 huruf (d) Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 Tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan menyatakan “Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang
selanjutnya disebut THR, adalah pendapatan
pekerja yang wajib dibayarkan oleh
Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang
berupa uang atau bentuk lain”.
Penekanan dari definisi ini ialah, THR itu merupakan bagian dari pendapatan
pekerja, artinya seorang pekerja selain memperoleh pendapatan berupa gaji
pokok, tunjangan dan lain-lainnya, juga mendapatkan pendapatan dari THR.
Kemudian penggalan kalimat “wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja”
menurut saya merupakan penekanan sekaligus penjelasan makna kata “pendapatan”
yang digunakan di dalam definisi ini, sebab jika tidak wajib maka kata yang
lebih tepat ialah “pemberian”. Selain itu yang harus diperhatikan juga dalam
definisi ini ialah bentuk THR itu tidak selamanya dalam bentuk uang saja namun
dapat pula dalam bentuk lain seperti misalnya sembako, namun dengan ketentuan
dan syarat-syarat tertentu.
Kemudian
di dalam definisi tersebut yang wajib memberikan THR adalah ‘pengusaha’ dan
yang berhak menerima THR adalah ‘pekerja’, sehingga pertanyaan selanjutnya yang
muncul ialah, siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pengusaha dan pekerja?.
Apakah pemilik CV bisa dikategorikan sebagai pengusaha?. Atau hanya pemilik
Badan Hukum seperti PT (Perseroan Terbatas) saja yang dapat dikategorikan
sebagai pengusaha?. Karena kita sedang membicarakan THR maka dasar untuk
membahas dan menjawab permasalahan tersebut haruslah berdasarkan aturan
perundang-undangan yang mengatur tentang THR, karena jika membuka seluruh
literatur yang ada, maka akan banyak sekali definisi dan makna kata ‘pengusaha’
dan ‘pekerja’ yang kadang kala bertentangan satu dengan yang lainnya.
Yang
dimaksud dengan pengusaha ialah:[6]
- Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang berkedudukan di luar Indonesia.
Jadi
ada tiga yang dikategorikan sebagai pengusaha yakni: Orang, Persekutuan, dan
Badan Hukum. Orang berarti manusia yang tentunya sebagai subyek hukum,
Persekutuan berarti perkumpulan atau contoh konkritnya seperti pemilik CV, dan
terakhir Badan Hukum[7]
seperti PT, Yayasan, dll. Kemudian syarat selanjutnya ialah, ketiganya harus
menjalankan sebuah perusahaan agar dapat dikategorikan sebagai pengusaha. Namun
pertanyaannya ialah apa yang dimaksud atau termasuk kedalam kategori sebagai ‘perusahaan’
?. Di dalam Pasal 1 huruf (a) Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun
1994 dinyatakan: “Perusahaan adalah
setiap bentuk usaha yang menpekerjakan pekerja dengan tujuan mencari
keuntungan atau tidak baik milik
swasta maupun milik Pemerintah”. Di dalam definisi ini tegas dikatakan bahwa
perusahaan adalah ‘bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja’. Artinya perusahaan
yang dimaksud di sini tidak berarti harus sebuah badan hukum, namun badan usaha
seperti firma, CV, atau UD juga termasuk di dalamnya. Hal ini tentunya penting
mengingat agar pengusaha tidak berlindung dengan status perusahaan yang
dimilikinya.
Kemudian
untuk ‘pekerja’ sendiri telah didefinisikan dengan singkat dan jelas di dalam
Pasal 1 huruf (c) Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 yang
dinyatakan “Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha dengan
menerima upah”. Ketentuan ini terlihat cukup sederhana dan pasti mudah
dipahami, tentunya dengan dasar tafsir yang sederhana dan tidak mengutak -
atiknya dengan tafsir yang terlalu
ideologis.
Ketentuan umum
pemberian THR
Karena
THR ini jelas menyangkut dengan hari raya keagamaan maka pemberiannyapun
tergantung dan berpatokan dengan hari raya keagamaan. Pasal 2 ayat (2) Permen
Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 menyatakan “THR sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 diberikan satu kali dalam satu tahun”. Tentu akan menjadi
pertanyaan jika pasal ini tidak ada, mengingat hari raya keagamaan bisa saja
berlangsung beberapa kali dalam satu tahun. Umat Islam misalnya, yang merayakan
Idul Fitri dan Idul Adha dalam satu tahun hijriah, saya kira umat agama lainnya
juga demikian, sehingga ketentuan tentang THR hanya mengikat pengusaha satu
kali dalam satu tahun, misalnya untuk umat Islam diberikan hanya untuk hari
raya Idul Fitri saja dan tidak diberikan pada saat hari raya Idul Adha.
Kemudian kata ‘Tahun’ di dalam pasal ini memang dapat dipertanyakan apakah yang
dimaksud ialah tahun masehi, hijriah, atau perhitungan tahun menurut agama
lainnya, yang tentu memiliki perbedaan perhitungan. Namun meskipun memiliki
perbedaan perhitungan, belum penulis temukan ada perhitungan tahun menurut
agama yang diakui di Indonesia yang jumlah 1 tahunnya sama dengan setengah
tahun masehi, sehingga hal ini tidaklah menjadi masalah yang mendasar.
Kemudian
ketentuan Pasal 2 ayat (2) di atas lebih dijabarkan kembali di dalam Pasal 4
ayat (1) Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 yang menyatakan “Pemberian
THR sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan Hari Raya
Keagamaan, masing-masing pekerja kecuali
kesepakatan pengusaha dan pekerja menentukan lain”. Sehingga perlu untuk
para pekerja memperhatikan kontrak kerja atau jika ada kesepakatan lainnya yang
kiranya mencantumkan ketentuan tentang pemberian THR. Karena tidak menutup
kemungkinan karena pengusaha tidak ingin disibukkan dengan mengelompokkan
karyawannya ke dalam kelompok agama masing-masing untuk pemberian THR, maka diseragamkan
pemberian THR dilakukan setiap tanggal 30 Desember setiap tahunnya. Ketentuan
seperti ini jika disepakati bersama antara pengusaha dengan pekerja, maka akan
mengikat kedua belah pihak, sehingga sekali lagi, sangat penting untuk
memperhatikan ketentuan THR yang ada di dalam kontrak kerja, ataupun di dalam
kesepakata lainnya. Kemudian selain argumentasi tafsir di atas, ada juga yang
memberikan tafsir bahwa boleh menentukan lain, namun harus tetap merupakan hari
raya keagamaan, misalnya dalam suatu perusahaan terdapat 500 orang pekerja, dan
terdiri dari 5 agama yang berbeda-beda, maka pengusaha boleh membuat
kesepakatan dengan pekerja untuk menseragamkan pemberian THR untuk 500 orang
pekerjanya hanya pada hari raya Idul Fitri terlepas karyawan tersebut beragama
apapun, dengan syarat harus disetujui oleh masing-masing pihak baik itu
pengusaha maupun pekerja. Oleh karena itu, menurut penulis di sinilah letak
multi tafsir terhadap pasal ini, yang tentunya memerlukan revisi yang lebih
baik agar tidak terjadi ketidak jelasan makna seperti ini.
Terhadap
batas waktu pembayaran sendiri, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permen Tenaga
Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994
yang menyatakan “Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib dibayarkan oleh pengusaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari
Raya Keagamaan. Secara sepintas pasal ini memiliki dua masalah. Yang pertama
yakni waktu tujuh hari tersebut terlalu singkat untuk melakukan pembayaran THR,
sebab jika terjadi kekurangan pembayaran atau tidak dibayarkan sama sekali,
maka waktu yang diperlukan sangat mepet untuk melakukan pengaduan padahal
tujuan pengaduan adalah untuk mendapatkan hak-hak pekerja berupa pembayaran THR
yang akan digunakan untuk hari raya, belum lagi jika dikurangi waktu mulainya
libur bersama, maka otomatis waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah
THR akan sangat singkat, sehingga menurut penulis waktu 7 hari sangatlah tidak
efektif. Masalah kedua yakni, bunyi Pasal 4 ayat (2) ini yang tidak isinya
dengan tegas menyatakan untuk memperjelas ketentuan Pasal 4 ayat (1) namun
isinya tidak lengkap jika dipasangkan unsur-unsurnya dengan pasal yang
diperjelasnya. Dikatakan di dalam Pasal 4 ayat (2) ini ialah “...
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan”, bagimana jika
ketentuan THR disepakati dalam waktu yang lain, tidak pada waktu hari raya
keagamaan, dan waktu pembayarannya berapa hari sebelum atau sesudah tanggal
kesepakatan itu ?. hal ini yang belum terlihat pengaturannya.
Yang Berhak dan Tidak Berhak
atas THR
Di
dalam Pasal 2 ayat (1) Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994
menyatakan “Pengusaha wajib
memberikan THR kepada pekerja yang
telah mempunyai masa kerja 3 bulan
secara terus menerus atau lebih. Mengingat ada PKWT dan PKWTT, kemudian
merujuk kepada definisi ‘pekerja’ sebagaimana yang telah penulis uraikan
sebelumnya, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini berlaku kepada seluruh karyawan
PKWT maupun PKWTT tanpa ada perbedaan dengan ketentuan masa kerja minimal 3
bulan secara terus menerus.
Kemudian,
ketentuan yang membedakan PKWT dengan PKWTT dalam pemberian THR terdapat di
dalam Pasal 6 ayat (1 dan 2) Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun
1994 yang menyatakan:
- Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan berhak atas THR.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pekerja dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu yang hubungan kerjanya berakhir sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan.
Makna
pasal di atas ialah, untuk PKWTT yang hubungan kerjanya berakhir dalam rentang
waktu 1 hari sampai 30 hari sebelum hari rata keagamaan maka dia berhak atas
THR. Namun untuk PKWT dia berhak atas THR jika masa kerjanya berakhir paling
tidak pada hari raya keagamaan atau melewati hari raya keagamaan, artinya untuk
PKWT tidak berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (1) di atas. Memang jika kita
mencermatinya, ini bisa menjadi celah untuk dipermainkan oleh pengusaha agar
terhindar dari kewajibannya membayar THR. Misannya dengan mencantumkan tanggal
berakhirnya PKWT sebelum tanggal hari raya keagamaan, mungkin cara ini terlihat
licik, namun harus diakui ini adalah celah yang tersedia atau disediakan oleh
peraturan yang ada.
Selanjutnya
jika dikaitkan antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 6 ayat (2) maka bisa saja
muncul perdebatan bahwa bagaimana jika PKWT yang masa berlakunya satu tahun
berakhir satu bulan sebelum hari raya keagamaan, kemudian diperpanjang lagi
untuk satu tahun berikutnya ?. Hal seperti ini dapat memunculkan beragam
tafsir, namun terlepas dari itu semua penulis akan mencoba melihatnya khusus
dari sudut pandang pribadi. Bahwa untuk hal seperti ini maka titik penentunya
ialah saat berakhirnya PKWT dan penpanjangan PKWT tersebut.
Jika
PKWT diperpanjang secara otomatis dengan adanya pemberitahuan dan kesepakatan
sebelum tanggal berakhirnya PKWT dan tanpa adanya jeda hari terkait dengan
berakhirnya dan diperpanjangnya PKWT maka pengusaha wajib membayarkan THR
kepada pekerja dengan asumsi bahwa telah terpenuhi unsur ‘masa kerja 3 bulan secara
terus menerus atau lebih’ sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1).
Ketentuan ‘masa kerja’ di dalam pasal ini tidak berarti harus dihitung dengan
masa kerja berdasarkan PKWT namun harus juga dilihat masa kerja secara nyata.
Karena jika kita menggunakan asusmsi bahwa ‘masa kerja’ yang dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) ialah harus sesuai dengan PKWT maka asusmsi yang sama juga
dapat diajukan bahwa tidak ada dasar hukum tentang keharusan untuk menghitung ‘masa
kerja’ berdasarkan waktu yang tercantum di dalam PKWT. Sehingga tidak ada dasar
yang mewajibkan ataupun melarang untuk menghitung ‘masa kerja’ dalam Pasal 2
ayat (1) harus berdasarkan PKWT, maka dari itu sudut pandang tafsir yang paling
mungkin yakni menghitung ‘masa kerja’ berdasarkan fakta nyata ‘masa kerja’
pekerja di perusahaan tersebut.
Namun
jika PKWT berakhir dan diperpanjang dengan memberikan jeda atau jarak meskipun
itu hanya sehari saja, misalnya PKWT berakhir tanggal 15 Juni 2014 kemudian
pengusaha dan pekerja sepakat menandatangani PKWT baru meskipun dikatakan itu
adalah perpanjangan PKWT lama namun tanggal mulai berlakunya tercantum tanggal
17 Juni 2014 dan hari raya keagamaan jatuh pada tanggal 30 Juni 2014, maka
pengusaha tidak wajib untuk membayarkan THR kepada pekerja. Asumsi ini
berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) bahwa ‘masa kerja 3 bulan secara terus
menerus atau lebih’, mungkin dapat dikatakan bahwa dia telah bekerja lebih dari
3 bulan di perusahaan tersebut, namun dia tidak bekerja secara terus menerus,
ada jeda antara PKWT pertama dan PKWT ke dua. Mungkin argumen ini akan dibantah
dengan menyatakan tidak cocok sebab alasan saya untuk ini mendasarkan pada PKWT
dan alasan pertama saya di atas tidak berdasarkan masa kerja di PKWT, namun
pandangan penulis untuk argumen pertama di atas karena tidak ada waktu kosong
atau jeda yang tersisa tanpa kekosongan status pekerja diperusahaan tersebut,
berbeda halnya dengan permasalahan kedua ini, yang mana terdapat jeda atau
kekosongan status pekerja di perusahaan tersebut, karena jeda antara
berakhirnya PKWT dan berlakunya PKWT baru tidak terdapat status pekerja di
sana. Berbeda halnya misalnya ketika pekerja tersebut sakit atau izin kerja,
maka statusnya tetap sebagai karyawan, namun ketika terjadi masa jeda atau
kekosongan seperti yang saya maksud di atas maka status sebagai karyawan tidak
dimilikinya. Oleh karena itulah saya berasumsi dengan kondisi demikian
pengusaha tidak diwajibkan untuk membayar THR.
Kemudian
Pasal 6 ayat (3) Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 mengatur
tentang hak atas THR terhadap pekerja yang dipindah kerjakan, yang mana
dinyatakan “Dalam hal pekerja dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja
berlanjut, maka pekerja berhak atas THR pada perusahaan yang baru, apabila dari
perusahaan yang lama, pekerja yang bersangkutan belum mendapatkan THR”. Menurut
penulis ketentuan ini jika ditafsirkan dengan sederhana maka cukup jelas hanya
saja yang perlu ditambahkan untuk penjelasan yakni masa kerja terhitung sejak
mulai bekerja di perusahaan lama ditambah dengan masa kerja diperusahaan baru
di tempat dipindahkan tersebut.
Yang Tidak Wajib
Memberikan THR Secara Penuh
Pasal
7 Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 mengatur tentang hal ini
yang mana di dalam ayat (1) dinyatakan “Pengusaha yang karena kondisi perusahaannya tidak mampu
membayar THR dapat mengajukan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah THR kepada Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan”. Dua
unsur yang sangat perlu untuk penjelasan dan dipahami terhadap Pasal 7 ayat (1)
ini. Yang pertama terkait dengan frase ‘besarnya jumlah THR’ artinya pengusaha
tidak bisa terhindar dari kewajiban pemberian THR ini, begitu juga meskipun
kita membolak balik ketentuan Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun
1994 tidak akan ditemukan satu pasalpun yang membebaskan pengusaha dari
kewajibannya membayarkan THR, karena ketentuan Pasal 7 ayat (1) ini hanya
memberikan keringanan terkait dengan “jumlah” THR yang wajib dibayarkan bukan
terkait dengan pembebasan kewajiban pembayaran THR. Yang kedua yakni terkait
dengan penjelasan unsur ‘kondisi perusahaan tidak mampu membayar THR’, tidak
dijabarkan kondisi seperti apa saja yang dimaksud, dan jika kita kaitkan dengan
Pasal 7 ayat (3) Permen
Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994
yang menyatakan “Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan menetapkan besarnya jumlah THR, setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan keuangan
perusahaan”, maka penentuan terkait dengan kondisi perusahaan apakah mampu
atau tidak membayar THR sepenuhnya merupakan pertimbangan dari Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan
berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan perusahaan, dan pemeriksaan keuangan
oleh siapa pun tidak dijelaskan apakah oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, pihak ketiga, atau laporan
perusahaan sendiri. Hal ini memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kemudian
Pengajuan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah THR kepada Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaa harus
diajukan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya Keagamaan yang terdekat.[8]
Bentuk dan Perhitungan
THR
Dalam
perhitungan THR maka kita mengacu kepada ketentuan Pasal 3 Permen Tenaga Kerja
dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 yang dalam ayat (1) dinyatakan:
Besarnya
THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut:
- Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah.
- Pekerja yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x 1(satu) bulan upah.
Selanjutnya
Pasal 3 ayat (2) menyatakan “upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah upah pokok di tambah tunjangan-tunjangan tetap”.
Contoh
perhitungannya misalnya:
Si
“A” bekerja di PT. ABC dengan memperoleh gaji pokok Rp. 2.500.000,-; Tunjangan transport
Rp. 500.000,-; dan Tunjangan jabatan Rp. 400.000,-
Jika
si “A” bekerja lebih dari satu tahun (15 bulan) maka THR si “A” sebesar satu
bulan gaji yakni Rp. 3.400.000,-
Jika
si “A” bekerja kurang dari 1 tahun (8 bulan) maka THR si “A” adalah 8/12 (satu
bulan upah) = 8/12 (Rp. 3.400.000,-) = Rp. 2.266.667,-
Kemudian
di dalam pasal 3 ayat (3) dinyatakan:
“Dalam
hal penetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK), atau Peraturan
Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau kebiasaan yang telah
dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka
THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja, Peraturan
Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan”.
Artinya
jika di dalam KK, PP, KKB, atau kebiasaan yang jumlah THR lebih besar daripada perhitungan
sebelumnya, maka jumlah yang lebih besar itulah yang berlaku.
Adapun
pasal 5 Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 mengatur tentang
bentuk THR yang mana dinyatakan:
- Dengan persetujuan pekerja, THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagian dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai THR yang seharusnya diterima”.
- Bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan bersamaan dengan pembayaran THR.
Contoh
misalnya:
Si
“A” bekerja di PT. ABC dengan memperoleh gaji pokok Rp. 2.500.000,-; Tunjangan transport
Rp. 500.000,-; dan Tunjangan jabatan Rp. 400.000,- dengan masa kerja lebih dari
satu tahun (15 bulan) maka THR si “A” sebesar satu bulan gaji yakni Rp.
3.400.000,-
Berdasarkan
Pasal 5 di atas jika ada persetujuan dari pihak pekerja maka pengusaha dapat
memberikan si “A” THR dalam bentuk uang kontan sebesar Rp. 2.550.000,- ditambah
dengan pakaian, minyak goreng, dan beras yang nilai totalnya sebesar Rp.
850.000,- dengan diberikan secara bersamaan.
Sangsi
Terkait
dengan sangsi bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR atau tidak membayar THR
dengan sesuai maka sangsi yang diterapkan sudah tidak ada lagi secara tegas.
Sangsi yang masih bisa dilakukan berdasarkan Permen Tenaga Kerja dan
Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 ini hanyalah berupa tindakan dari pengawas
ketenagakerjaan, yang mana tindakan itupun tentu akan sangat terbatas dan lemah
sebab tidak memiliki kekuatan memaksa dan masih tergantung penilaian pihak
pengawas.
Sebelumnya
Pasal 8 Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 ini mengatur
tentang sangsi yang hanya berupa pelanggaran[9]
dengan menyatakan: “Bagi pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) –
dan pasal 4 ayat (2), diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 17
Undang-Undang No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai
Tenaga Kerja”. Namun ketentuan tentang pasal ini tidak berlaku lagi karena UU
No. 14 Tahun 1969 telah dicabut dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.[10]
Selain itu meskipun UU No. 14 Tahun 1969 tetap berlaku ketentuan sangsinya
sangatlah lemah[11]
dan hanya dogolongkan kedalam pelanggaran saja.
Oleh
karena itu, diperlukan cara khusus untuk menangani kasus semacam ini (pengusaha
tidak mau membayar THR atau kurang membayar THR). Tidaklah memberikan efek jera
atau tekanan yang kuat jika hanya mengandalkan pengawas ketenagakerjaan saja. Namun
harus dengan stategi dan upaya-upaya tertentu agar pihak pengusaha bersedia
melaksanakan kewajibannya untuk membayar THR kepada orang yang dipekerjakannya.
Sehingga jika anda mengalami masalah THR silahkan konsultasikan terlebih dahulu
kepada penasehat hukum atau tim advokasi anda sebelum melakukan tindakan hukum
yang memungkinkan dan diperlukan.
Regards
Jun
[1] Tulisan
ini dibuat berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Permen Tenaga Kerja dan
Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja
di Perusahaan. Sehingga jika membaca Permen tersebut maka sama saja dengan
membaca tulisan ini, hanya saja ketentuan-ketentuan yang ada di dalam permen
tersebut yang penulis sedikit urai dengan bahasa sehari-hari yang biasa kita
gunakan agar lebih mudah dimengerti. Namun ada juga ketentuan-ketentuan yang
penulis tidak masukkan ke dalam tulisan ini. Silahkan jika ada kritik dan
saran.
[2]
Penulis adalah alumni dari Fakultas Hukum (Bagian Hukum Internasional) Universitas
Hasanuddin Makassar, merupakan Advokat Muda dan pendiri dari Lembaga Bantuan
Hukum Cahaya Nusantara, serta pemilik dan penulis seluruh artikel yang ada di blog ini.
[3] Memang
benar di dalam UU No. 13 Tahun 2003 ada beberapa pasal yang menggunakan kata
‘tunjangan’ seperti di dalam definisi tentang upah pada Pasal 1 angka (30), Pasal
94 tentang komponen upah, dan pasal 157 ayat (1), namun apakah yang dimaksud
dengan kata ‘tunjangan’ itu adalah Tunjangan Hari Raya atau tidak ?, hal
tersebut sangat tidak jelas, dan tidak terdapat pula penjelasan yang baik di
dalam penjelasan UU itu sendiri.
[4] Efektifitas
aturan perundang-undangan yang mengatur tentang THR jika hanya dengan Permen
maka jelas hal itu tidaklah dapat dikatakan efektif, sebab tidak ada unsur atau
ketentuan memaksa di dalamnya seperti misalnya ketentuan pidana jika pihak
pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar THR, hal ini jelas
tidak konsisten dengan definisi THR itu sendiri yang merupakan kewajiban pihak
pengusaha kepada pihak pekerja. Karena harus dicermati bersama bahwa jika kita
menyimak Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan maka ketentuan pidana hanya boleh dimasukkan di dalam UU,
Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Peraturan
Daerah Kabupaten Kota saja, ketentuan pidananya sangat lemah. Maka untuk
kedepannya permasalahan mengenai THR akan lebih efektif jika diatur di dalam
Undang-Undang, yang menurut penulis sangat disayangkan di dahulu ketika
penyusunan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan tentang THR
ini tidak dimaksukkan pdahal THR merupakan kewajiban dari pihak pengusaha.
[5]
Selain hanya berlaku untuk kalangan internal dan hanya merupakan himbauan,
Surat Edaran (SE) tidaklah termasuk ke dalam bagian dari peraturan
perundang-undangan, memang ini masih menjadi perdebatan di antara banyak
kalangan, namun jika merujuk kepada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011
Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: “Jenis
dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d.
Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Kemudian di dalam Pasal (8) UU yang sama
menyatakan: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah
atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa
atau yang setingkat”. Oleh karena itu, yang termasuk di dalam peraturan
perundang-undangan hanyalah peraturan perundang-undangan sebagaimana yang
tercantum di dalam Pasal 7 tersebut di atas ditambah dengan ‘peraturan’ yang
ditetapkan oleh lembaga terkait sesuai dengan Pasal 8 di atas. Dengan demikian
‘Surat Edaran’ jelaslah tidak termasuk di dalam bagian dari peraturan
perundang-undangan.
[6] Pasal 1
huruf (b) Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 Tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan
[7]
Ketentuan tentang Badan Hukum terdapat dalam Pasal 1653 KUHPerdata yang
menyatakan “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai
badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh
kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu
diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud
tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”.
Kemudian dalam bentuk nyata yang kita kenal, misalnya berupa PT, BUMN (Perum
atau Persero), BUMD, Yayasan, Koperasi, dll.
[8] Pasal 7
ayat (3) Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 1994 Tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.
[9] Ibid.,
Pasal 8 Ayat (2).
[10] Lihat
Pasal 192 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
[11]
Pasal 17 ayat (2) UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Mengenai Tenaga Kerja menyatakan “Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1)
dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman
kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)”.